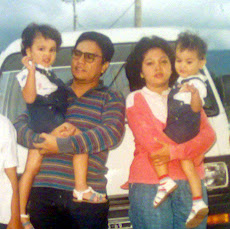Kau duduk di depanku. Lurus dan persis. Jendela lebar menampung puncak-puncak pohon pinus dan melemparkannya utuh ke atas meja. Di atas taplak berbunga, helai dan serat daunnya bercampur dengan air mineralku dan juice alpukatmu, dengan steak sapimu dan pofertjes-ku.
Kupandangi matamu penuh. Senja sudah turun sejak tadi. Lelampu rumah-rumah penduduk di pelataran datar mulai nyalang. Angin terdiam, malas merambat. Duduk di sofa berbentuk huruf U, kuhirup bau malam saat matamu mengecil setiap tertawa. Lucu dan cantik, membuat kumerasa, di umur hidup kita, aku ingin menyayangimu.
Hanya saja, aku tak akan menyentuhmu. Kularang jari-jariku. Di temaram langit yang berkabut, aku cuma ingin paparkan rasa. Pekan-pekan belakangan ini, kita terlalu hanyut dalam amuk. Perjumpaan kita tidak lagi hanya peristiwa kasih, tetapi terus menggelora. Kita larut terbawa jauh di pusaran jingga, terengah-engah dengan deru napas memburu. Kau mendekapku dalam, aku menyusup masuk ke liang tubuhmu. Aku menikmatimu, kau menikmatiku, dalam rengkuh indah alami universal anak manusia.
Tapi malam ini, di sini, aku mau duduk seperti ini. Menikmati keindahan dalam mematai caramu bersikap. Senyum yang melebarkan bibir. Tawa yang membuat hidungmu berkernyit. Duduk tanpa berbuat apa-apa. Cuma kalimat yang perlu dilontarkan. Karena kita harus lebih banyak bicara. Tentang apa saja. Tentang langit kelabu dan bulan tunggal di atas sana, mengenai ranting-ranting dan burung pulang malam, atau malam teduh dan dingin yang meraba-raba leher.
Airmataku tetes. Feeling guilty. Tak layak aku membawamu ke sana, saat cinta dikalahkan passion dan gerumas membunuh usapan. Kita harus kembali cepat-cepat, sebelum kita tersesat dalam kabut. Kau tersedak, menahan isak yang akan meledak. Hujan tersendat, membekukan jemari dan lidah. Angin menampar.
 Malam di atas bukit. Sinar bulan yang panjang ke ujung utara. Kau duduk di hadapanku, mulai ikut menitikkan airmata. Merasa lemah, kehilangan daya. Kau mencinta, tapi tak bisa berbuat apa-apa. You like to break the chain I put around you, but you know you never will. Tapi aku tak lantas memelukmu. Ditengahi oleh sekuntum ros merah nyalang, kita terus bertatap dengan mata kucing sakit.
Malam di atas bukit. Sinar bulan yang panjang ke ujung utara. Kau duduk di hadapanku, mulai ikut menitikkan airmata. Merasa lemah, kehilangan daya. Kau mencinta, tapi tak bisa berbuat apa-apa. You like to break the chain I put around you, but you know you never will. Tapi aku tak lantas memelukmu. Ditengahi oleh sekuntum ros merah nyalang, kita terus bertatap dengan mata kucing sakit.
Crystal, kita sedang mencari jalan ke arah hubungan yang sehat. Memberi dan menerima dalam arti yang sakral. Tetapi sulit sekali. Karena akhirnya, ketika berdiri di ketinggian dalam melempar pandang ke ambal muram berlampu di bawah sana, yaitu saat kulingkarkan kedua tangan memeluk tubuhmu dari belakang, kau tetap memaling wajah untuk mengecup bibirku.
Dan embun pun turun. Cinta ternyata tak bisa berdiri sendiri. Selalu ada passion di dalamnya. Riuh menggelora, nikmat menakutkan.
Kupandangi matamu penuh. Senja sudah turun sejak tadi. Lelampu rumah-rumah penduduk di pelataran datar mulai nyalang. Angin terdiam, malas merambat. Duduk di sofa berbentuk huruf U, kuhirup bau malam saat matamu mengecil setiap tertawa. Lucu dan cantik, membuat kumerasa, di umur hidup kita, aku ingin menyayangimu.
Hanya saja, aku tak akan menyentuhmu. Kularang jari-jariku. Di temaram langit yang berkabut, aku cuma ingin paparkan rasa. Pekan-pekan belakangan ini, kita terlalu hanyut dalam amuk. Perjumpaan kita tidak lagi hanya peristiwa kasih, tetapi terus menggelora. Kita larut terbawa jauh di pusaran jingga, terengah-engah dengan deru napas memburu. Kau mendekapku dalam, aku menyusup masuk ke liang tubuhmu. Aku menikmatimu, kau menikmatiku, dalam rengkuh indah alami universal anak manusia.
Tapi malam ini, di sini, aku mau duduk seperti ini. Menikmati keindahan dalam mematai caramu bersikap. Senyum yang melebarkan bibir. Tawa yang membuat hidungmu berkernyit. Duduk tanpa berbuat apa-apa. Cuma kalimat yang perlu dilontarkan. Karena kita harus lebih banyak bicara. Tentang apa saja. Tentang langit kelabu dan bulan tunggal di atas sana, mengenai ranting-ranting dan burung pulang malam, atau malam teduh dan dingin yang meraba-raba leher.
Airmataku tetes. Feeling guilty. Tak layak aku membawamu ke sana, saat cinta dikalahkan passion dan gerumas membunuh usapan. Kita harus kembali cepat-cepat, sebelum kita tersesat dalam kabut. Kau tersedak, menahan isak yang akan meledak. Hujan tersendat, membekukan jemari dan lidah. Angin menampar.
 Malam di atas bukit. Sinar bulan yang panjang ke ujung utara. Kau duduk di hadapanku, mulai ikut menitikkan airmata. Merasa lemah, kehilangan daya. Kau mencinta, tapi tak bisa berbuat apa-apa. You like to break the chain I put around you, but you know you never will. Tapi aku tak lantas memelukmu. Ditengahi oleh sekuntum ros merah nyalang, kita terus bertatap dengan mata kucing sakit.
Malam di atas bukit. Sinar bulan yang panjang ke ujung utara. Kau duduk di hadapanku, mulai ikut menitikkan airmata. Merasa lemah, kehilangan daya. Kau mencinta, tapi tak bisa berbuat apa-apa. You like to break the chain I put around you, but you know you never will. Tapi aku tak lantas memelukmu. Ditengahi oleh sekuntum ros merah nyalang, kita terus bertatap dengan mata kucing sakit.Crystal, kita sedang mencari jalan ke arah hubungan yang sehat. Memberi dan menerima dalam arti yang sakral. Tetapi sulit sekali. Karena akhirnya, ketika berdiri di ketinggian dalam melempar pandang ke ambal muram berlampu di bawah sana, yaitu saat kulingkarkan kedua tangan memeluk tubuhmu dari belakang, kau tetap memaling wajah untuk mengecup bibirku.
Dan embun pun turun. Cinta ternyata tak bisa berdiri sendiri. Selalu ada passion di dalamnya. Riuh menggelora, nikmat menakutkan.
Cuplikan dari rancangan novel Crystal, 11 Juni 2004