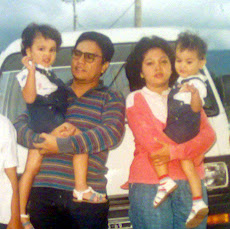Telah tiga tahun aku belajar menikmati napasmu. Inilah kemampuan mutakhirku, dapat memahami perasaanmu hanya dengan mendengar aliran udara masuk dan alunan udara keluar melalui hidung tirusmu. Gelombang dada dan perut yang turun naik, kini lebih mengartikan gejolak rasa dan kondisi hatimu.
Sebelum hari yang menjatuhkan vonis itu, aku tak pernah mengerti semua ini. Bahkan kedip matamu tadinya cuma bernilai biasa. Komunikasi kita tak bersandar pada isyarat, walaupun dulu saat di Kampus Taman Sastra UI, beberapa pekan setelah kita berkenalan, aku rajin menunggu matamu berkedip, sebagai tanda kau sedang berusaha mengantarkan rasa. Tapi kau tak memberiku gelombang magnetis itu. Kau bukan pria genit yang nakal. Kau serius, tak memerlukan gesture untuk melahirkan cinta.
“Kita punya kalimat,” demikian kiranya maksud hatimu. Mengikut alur itu, aku lantas percaya pada kedahsyatan huruf. Kau mahir dalam berkata. Terkesan atas kekuatan susunan kalimatmu yang mampu menyihir para mahasiswa, aku memujamu setinggi hati. Dan menerimamu sebagai pasangan hidup, ketika batin kita terhubung oleh gelombang rasa yang sama. Maka pada hari ke delapan, bulan ke delapan dan era tahun 1900 yang ke-88, kita ucapkan ikrar berumahtangga, saling mengasihi, saling menghargai, saling menjaga. Kita janjikan: akan selalu bersama, dalam sedih dan gembira, dalam sakit dan sehat, sampai kematian datang memisah.
Vic, every moment spent with you is a moment I treasure.Aku tak ingin semuanya berakhir. Tak ingin pisah darimu. Seandainya kematian memang bisa ditangkal, aku ingin ada di sampingmu sepanjang usia bumi. Di ruas hatiku, getar jiwamu tak akan pernah memudar. Kaulah harta karun bagiku dan bagi Adilla Paramarta, putra semata wayang kita yang sedang beranjak remaja. Engkau selalu menempati relung-relung batin kami.
Sekarang ini, kami memang sudah kehilangan kalimat-kalimatmu dan kefasihanmu berkata. Semua dialog verbal mendadak nol. Semua dirampas pada Selasa penghujung Mei tiga tahun lalu. Palu godam raksasa yang menghantam, menghenyakku sehingga tak lagi bisa bersuara. Menurut cerita temanmu, sore tatkala kau menguji mahasiswa-mahasiswa S3 di Kampus Universitas Indonesia Salemba, kepalamu mendenyutkan rasa sakit yang hebat. Oleh karena itu kau lantas keluar, gontai berjalan menuju ruang dosen untuk meredamnya dengan rokok, kopi dan istirahat.
Menurut cerita mereka, sempat terdengar ada suara gelas pecah di ruang tempatmu mengaso, membersit lewat kisi-kisi dan sempat disimak oleh penjaga ruang kuliah. Namun Pak Tua itu tidak berani membuka pintu. Baru sekitar setengah tujuh malam, dosen temanmu menemukan kau tergeletak lesu di lantai, di antara kursi meja yang kaku. Kau lemah dan tak punya daya. Mereka melarikanmu ke Rumah Sakit St. Carolus, langsung ke Unit Gawat Darurat. Tapi kau tetap tak sadar diri. Aku yang datang dengan kepanikan memelukmu dengan tangis panjang.
Papa, I just want to hold you close and feel your heart so close to mine.Kaulah cinta yang terbaring dalam selimut putih dengan selang-selang alit yang memenuhi kujurmu. Kau diam, tidak ada bebunyian. Wajahmu datar, tiada mimik. Tanganmu tak bergerak, tanpa
gesture yang bisa diartikan. Begitu sampai malam. Dan kami tak bisa membiarkanmu terus begitu, tak boleh menunggu berlama-lama. Upaya harus digencarkan dan keputusan harus diambil.
Menjelang dinihari kami boyong kau ke Tangerang, menuju Rumah Sakit Siloam Gleneagles di Karawaci. Kondisimu membuat aku seperti orang gila, Pa. Kata para ahli, pendarahan di batang otak yang kau alami tidak bisa dioperasi. Apalagi sempat terdengar prediksi, secara medis kemungkinan hidupmu cuma tinggal lima persen. “Tanpa mendahului Tuhan, secara medis kemungkinan hidup Victor cuma lima persen. Dan jika pun tetap bertahan hidup, ia akan mengalami kelumpuhan,” kudengar itu selentingan, karena tak ada yang berniat mengatakan kepadaku secara terbuka.
Lima persen? Apakah itu berarti kematianmu sudah 95 persen? Oh Tuhan, ternyata kita cuma manusia rentan. Suamiku rebah tak bergerak, terjerembab dalam batas ambang sadar-tidak sadar, menerawang dalam keanehan rasa, menyatu dengan dunia yang tak pernah kukenal. Di ranjang putih itu aku memandang wajah pucat. Mana kegairahannya, ya Allah!
Vic, just stay here in this moment, for all the rest of time. Kau terbaring dengan mata mengatup, layak nyenyak tidur, sentosa tanpa gangguan mimpi. Aku menatap wajah yang letih. Sayangku, kau memang terlalu capek beberapa bulan terakhir ini. Pekerjaan sebagai dosen saja sudah membuatmu sangat kaku dengan waktu, lebih lagi setelah ditambah dengan konsekuensi dari posisi sebagai Ketua di Komisi Penyiaran Indonesia. Perjalanan melintas khatulistiwa menuju pelosok kawasan Indonesia dan luar negeri membuat pikiranmu banyak terkuras.
Tapi aku tidak mengesalkan semua itu. Sungguh aku tak berani menyesali sesuatu, yang cuma akan membuatku jadi makhluk yang tak pandai bersyukur atas pemberian Maha Kuasa. Aku hanya tau, akhir-akhir itu, waktu kita sudah mulai terkikis. Makan malam keluarga sering terlewati. Aku yang mengerti akan semangat dan idealismu memang tak pernah mencemburui apapun, kecuali menyangsikan kesehatanmu. Bayang-bayang sayu yang menaungi pijar bola matamu, membuatmu terlihat lebih tua dari usia sesungguh.
Deru perangkat
air-conditioning di Gleneagles terasa menusuk. Papa kedinginankah? Tapak kakimu dingin. Tetapi kau mungkin tak merasanya, karena saat ini kau sedang berjalan-jalan di awan, berdialog dengan teman-teman di sana. Bukankah kau punya kawan di mana-mana? Jantung terus berdegup dan bibirmu yang kelu sesekali terlihat seperti mengambangkan senyum. Apakah kau sedang menyaksikan malaikat-malaikat bersayap putih menari dengan iringan harpa dan biola, atau jiwamu merasa nyaman mendengar doa-doa yang kami bisikkan, merambat masuk ke liang telinga dan hinggap di ruang kesadaranmu?
I’m feeling your heart beating and wondering what you're dreaming. Betapapun berat penyakit yang kau derita, aku tak akan pernah bisa melepasmu. Kami tidak siap. Adilla kita masih kecil, Vic. Begitupun, dia sangat mengerti tentang Papa-nya. Sangat care, anak baik yang tau gelagat, pintar membaca situasi. Dia menjalani hari-harinya dengan ketabahan yang tidak dipunyai anak lain. Sekolahnya tidak terganggu meski aku tau sebagian besar perhatiannya terpusat kepadamu. Anak pintar itu dalam beberapa waktu lagi akan berangkat ke manca negara, mengikut program pertukaran siswa ke luar negeri. Wah, dia persis sepertimu juga, gagah melangkah ke masa depan dan selalu menomorsatukan ilmu. Dialah Akasia yang teguh berdiri, besar menaungi lingkar jalan di depan Rumah Sakit tempatmu dirawat.
Diam-diam, aku berlindung di bawah bayangnya. Itu karena aku, sering-sering kini, merasa lebih rapuh. Kami sering bergenggaman jemari saat membezukmu, menunggu pijar matamu mengerling, menanti gerak jemarimu berkata, berharap senyum tipismu mengambang dan menunggu
gesture yang pas sesuai dengan gejolak jiwamu. Kami tau kau masih terus menggemakan kalimat-kalimat, cuma telinga kecil kami tak sanggup menangkap frekuensi suara dan tak punya daya untuk mengartikan sinyalmu.
“Kita tak punya kalimat,” demikian seakan-akan matamu berkata. Kini kita bersandar pada gerak, aba-aba, atau apapun namanya. Gerakan jempol kanan untuk mengiyakan, gerakan telunjuk kiri untuk menidakkan. Atau sebaliknya. Yang mana saja,
it will do, asal kita saling tau. Aku akan sangat berbahagia jika kau mengerti bahwa kami semua masih dan sangat menyayangimu.
I could spend my life in this sweet surrender, I could stay lost in this moment forever.Wewangi pinus menusuk tipis. Ada rasa akrab. Tetapi buru-buru kutepis pikiran itu. Kata orang-orang tua, tidak boleh menyukai rumah sakit. Karena rumah sakit bukan tujuan. Tidak ada orang yang bercita-cita berdiam di rumah sakit. Kecuali dokter. Menjadi pasien pasti bukan tujuan. Kau juga tak boleh menjadi pasien selamanya. Melihat semangat hidupmu yang tinggi, aku seakan memiliki keyakinan dan sangat ingin melihatmu bangkit berdiri, melangkah menggamit dan mengajakku berdansa dengan walza Strauss yang agung. Ingat saat-saat itu, sayang? Aku dalam pelukmu, kau utuh dalam dekapanku, dan kemudian kau kecup mataku.
Then I kiss your eyes, and thank God we're together.Indah keinginan itu, meski aku tau, keinginan itu layak gelembung-gelembung sabun yang mudah pecah. Para ahli telah mengatakan, kesembuhanmu hampir mustahil. Dengan keringkihan saat ini, setiap saat kau bisa menjauh dari kami. Tapi aku percaya mukjizat.
The miracle is not to fly in the air, or to walk on the water, but to walk on the earth. Ungkapan bijak dari Cina itu memagutku untuk mempercayai, kesembuhan orang-orang yang sakit bukanlah cuma tindakan manusia semata, tetapi karena gerak jemari Tuhan. Dan itu bisa terjadi terhadap siapa saja. Terhadapmu. Karena itulah kau lantas kubawa pulang, kembali ke rumah kita, untuk tidur bersama dengan Adilla di bawah atap yang sama, di dua kamar luas yang
berhubungan terbuka.
I just want to stay with you in this moment forever and ever.
Nothing’s impossible. Karena kemustahilan cuma milik orang-orang yang tidak percaya dan tidak berusaha. Padahal sinyal-sinyal, betapapun kecil, pastilah selalu ada. Itu pulalah yang tergambar pada 30 Mei lalu, saat kau genap tiga tahun dalam masa pasca stroke. Wajahmu cerah, segar dan -sungguh!- terlihat tambah muda. Puspa mengelopak dalam sanubari, ketika untuk pertama kali kau bisa melirik ke kanan, ke arahku yang berada di sisi tempat tidur. Dokter pernah memberitahu agar menanti lirikanmu. “Itu mengartikan kaki dan tangan di arah lirikan tidak lumpuh, dan secara teori akan bisa bergerak suatu saat nanti,” ujarnya.
Ya Tuhanku seorang, sangat besar arti lirikan itu. Terlalu mulukkah mimpi ini, jika di sudut batin terdalam aku menyimpan harap agar kita kembali seperti sediakala, Vic?
If you’re heart is in your dream, there’s no request is too extreme, anything your heart desire, will come to you. Jangan cerca aku jika meletak harapan di bintang tertinggi, karena dalam pengamatan detik ke detik, aku melihat otot lehermu yang semakin kokoh. Kau kini bisa mengangkat sendiri kepala yang menunduk saat duduk di kursi roda.
We wish upon a star, aku dan Adilla. Begitu selalu, juga pada saat suatu malam menunggu kantuk, tunggalku itu memanggilmu dari kejauhan.
“Papa, tickle my back! Tickle my back,” begitu dia berujar berkali-kali, seperti kebiasaannya dulu menjelang tidur, ketika kau sering menggelitiknya. Dilla juga mengenang ketika di pagi hari kau selalu membangunkan dengan menyentuhkan bulu mata ke kujur tubuhnya dan mencontohkan ke pipiku.
Inilah rindu. Kangenan yang panjang dan belum berujung. Kau masih belum pulih dan doa kami belum menemu jawab. Namun kuharap kau mampu meresapkan kerinduan Dilla di ruang
memory, agar canda itu bisa menyemangatimu untuk kembali ke masa kini. Bukankah kau selalu memiliki daya juang yang luar biasa?
I don't want to close my eyes and I don't want to fall asleep.Kau masih berbaring dengan mata mengatup, layak nyenyak tidur, sentosa tanpa gangguan mimpi. Akan kubiarkan kau begitu, terus menjaga dengan janji tidak akan jatuh terkantuk. Aku ingin menyelam di hatimu yang hijau damai, sebab ada nuansa damai di situ. Dan jika nanti kau terjaga dengan kelopak mata membuka, aku akan menerobos bola matamu untuk sampai di pelosok kamar-kamar batinmu. Aku ingin lihat di sana, sesungguhnya semua utuh seperti dulu. Kau masih Victor-ku dengan lisan yang fasih dan daya dengar yang peka.
Cuma kini, bahasamu sudah beda, lain dengan orang-orang sekitarmu. Tak ada yang mengerti bahasa yang kau pakai. Tapi aku akan membuka rahasia itu dengan mengartikan segala gerak kecilmu. Novelis Turki Orhan Pamuk bilang, di atas segalanya, kita harus memberi perhatian kepada bahasa tubuh yang membuat kita jadi manusia. Karenanya, kita tak harus bercakap-cakap lagi. Kasih yang ada menyebabkan kita tak butuh huruf dan suara, hanya mata yang saling berpaut dalam sorot penuh arti, cukup membuat kita hidup dalam kebahagiaan yang abadi. Seperti lidah dalam rongga mulut, cinta itu selalu ada, walau kita tidak sering merasakannya. Begitu juga segala ketulusan kita, aku buatmu, kau buatku.
Victor sayangku, I don't want to miss a thing.......