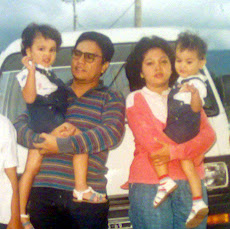Penulis :
IzHarry Agusjaya MoenzirPewawancara : IzHarry Agusjaya Moenzir & Nurhalim Tanjung
Foto Ilustrasi Sampul : Iskandar Leonardi
Penyunting : R. M. Subanindyo Hadiluwih, SH, MBA
Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Diterbitkan oleh : Institut Bina Bisnis Indonesia (IBBI) & Perhumas, Medan
Cetakan Pertama, Maret 1997
Dicetak oleh : PT Satria Deli Perkasa
________________________________________________________________________________
.......Buku ini sepenuhnya saya persembahkan buat istri tercinta, Aisyah Rahman Hasibuan, yang kobaran semangatnya selalu saya kagumi. Terimakasih atas hidup yang bernilai, atas kesetiaan, keindahan dan kebahagiaan, Tanpa Aisyah, saya tidak mungkin menjadi seorang Hadibroto.
- Prof. DR. H. S. Hadibroto, Medan, 8 Oktober 1996
________________________________________________________________________________
1. Layak Sepur di Atas Rel
Subuh merekah, mengusir malam gelap yang basah. Dan adzan dari masjid di sudut jalan sudah terdengar nyaring membangunkan. Langit di Timur mulai memerah, pertanda matahari sebentar lagi akan menyembulkan diri. Pepohonan masih gelap, jalanan masih sepi. Cuma sesekali terdengar langkah terburu-buru dari beberapa orang yang ingin mengejar sholat subuh di masjid.
Seperti biasa di musim penghujan, matahari selalu malas menyorotkan cahaya. Dengan lemah sinarnya akan mencoba menembus kerapatan dedaun bambu yang bergesekan satu sama lain, untuk menghalau embun yang tiarap di rerumputan.
Suasana gerimis pagi itu pastilah sangat sejuk, apalagi angin semilir berhembus masuk melewati ventilasi, merasuk hingga di tempat tidur, membuat banyak orang enggan bangkit untuk memulai harinya. Tidur pasti lebih enak.
Namun tidak demikian halnya di rumah saya di Pekalongan. Meski dingin sering membuat hati ingin berpeluk dengan bantal dan guling, bahkan meninggikan selimut hingga ke jakun, namun kebiasaan di rumah kami tidaklah demikian.
“Bangun Dji! Mandi. Nanti keduluan matahari.”
Demikian biasanya ibu membisikkan ucapan selamat paginya di telinga saya. Dia lantas menguakkan tirai, membuka jendela dan sebelum keluar, menyapa lagi.
“Hayo, nanti ketinggalan Mas-mu.” ujarnya.
Meski sering malas, tetapi saya pasti akan beringsut bangun. Bagi kami hal itu merupakan awal kegiatan harian yang tak boleh dirubah. Ianya sudah ada dan diberlakukan sejak lama, mungkin sejak saya belum lahir. Suasana pagi selalu hiruk pikuk dan sibuk. Tidak ada malas-malasan atau mengantuk yang berlebihan. Semuanya ligat membuka hari, berebutan ke kamar mandi, berlarian ke masjid.
Adalah ibu yang selalu membiasakan kami dengan hal-hal seperti itu. Bangun pagi, berwudhu untuk kemudian sholat, sudah menjadi salah satu dari beragam menu kehidupan keluarga Brotosuwignyo. Tidak ada yang mengeluh atau mengomel. Mempersoalkan juga tidak. Apalagi ribut-ribut dan protes. Meskipun hal itu bukan peraturan resmi, namun kami menjalankannya dengan rela dan sukacita, layak sepur di atas rel yang berjalan sesuai arahan.
Setelah membangunkan saya, biasanya ibu akan bergegas ke dapur untuk memasak air. Sudah dapat dipastikan, seceret teh manis akan diraciknya. Untuk ayah, segelas besar kopi tubruk yang rada pahit akan terhidang, persis tatkala beliau selesai berolahraga pagi.
Bagi ayah, segelas besar kopi di pagi hari adalah suatu kemewahan yang sangat pribadi. Jarang sekali dia memperoleh keistimewaan begitu di tempat lain. Sebagai pegawai kantor keuangan yang selalu dihadapkan pada masalah uang dan belasting, kesibukannya tak bisa diukur dari jumlah jam. Daerah pekerjaan kontrolir pajak selalu menerobos daerah-daerah pelosok, dan tak ada waktu buat kopi barang secangkir.
Kopi yang tersuguh adalah perlambang kecintaan isteri kepada suami. Mungkin demikian adanya, sehingga ibu tak pernah lupa. Cuma, tidak setiap hari ayah bisa menikmati kopi buatan ibu. Dalam sebulan, barangkali hanya enam-tujuh kali saja, karena selebihnya dia berada di pedalaman.
Meski berdomisili di Pekalongan, namun seperti saudara-saudara yang lain, saya dilahirkan di Tegal, pada 29 Maret 1919. Menurut ibu, sudah menjadi keharusan baginya untuk pulang ke Tegal jika saat melahirkan tiba.
Di Tegal, wanita yang bernama Siti Chasanah ini akan merasa lebih nyaman. Konon, keluarga Haji Abdul Hamid yang berdiam di Gili Tugel 12 itu, punya macam-macam cara untuk meladeni puterinya yang akan melahirkan cucu bagi mereka.
Kehamilan, bagaimanapun juga tetap merupakan suatu peristiwa sakral yang musti punya upacara-upacara tersendiri, demi keselamatan jabang bayi dan ibunya. Banyak yang dipantangkan, tetapi banyak juga yang diharuskan sebagai syarat.
Wanita berbadan dua pantang makan di depan pintu, sambil berjalan, dan sekali-kali tidak boleh makan di waktu magrib. Sementara yang diharuskan juga banyak, seperti mengantun¬gi benda tajam dan mandi bunga. Wanita hamil juga mengenal upacara mitoni, yaitu pada saat usia kehamilan mencapai tujuh bulan. Untuk keselamatan semuanya, akan dibuatkanlah tumpengan atau bancakan yang berisi sayur-mayur dengan segala sesuatu yang berada di alam. Bancakan itu lantas dikirimkan kepada keluarga, kerabat dan tetangga untuk disantap.
Karena cuma numpang lahir, Tegal bagi saya bukanlah kota yang punya banyak kenangan. Paling-paling tempat itu hanya mengingatkan saya akan saat-saat bermanja pada Mbah Kaji Kakung dan Mbah Kaji Puteri.
Sesungguhnyalah mereka keluarga santri yang saleh. Sebutan Kaji yang saya gunakan untuk memanggil mereka berasal dari kata Haji, sebagaimana lazimnya orang-orang sekampung memanggil mereka dengan rasa hormat.
Dari kakek dan nenek pihak ibu inilah saya memperoleh dasar-dasar Islam yang kukuh. Mereka, dalam setiap kesempatan, selalu menyuguhkan kami cerita-cerita tentang Nabi Muhammad S.A.W. Terutama bila Ramadhan telah tiba. Pada saat-saat seperti itu, sembari menunggu beduk magrib, mereka akan duduk di kursi goyang teras depan, dan kami berselonjor di lantai, menyimak apa yang disampaikan.
Dengan modal agama Islam yang kuat, saya memulai pendidikan dini dengan bersekolah di Hollands Inlandse School (H.I.S). Status dan kedudukan ayah yang cukup baik membuat saya bisa bersekolah di tempat yang mendingan itu. Kata ibu, anak pintar harus mendapat pelajaran yang bagus, dan boleh belajar di sekolah Belanda.
Benarkah saya anak yang pintar? Saya tidak menyadarinya. Angka rapport saya memang tidak ada enam-nya, semua tujuh ke atas, bahkan ada yang ponten sepuluh. Padahal saya tak belajar banyak dan tak menghapal banyak. Apa adanya saja. Bagi saya itu wajar dan lumrah, layak sepur di atas rel yang berjalan sesuai arahan.
Ibu tampaknya senang dengan keberadaan kami. Meski ayah selalu ke daerah-daerah terpencil, ibu tak pernah merasa sepi. Dialah tipikal wanita Jawa yang lugu. Swargo nunut, neroko katut. Selagi di dunia, jadi isteri, melahirkan keturunan. Kemudian masuk dapur, masak. Cuci baju lantas seterika. Mendidik anak. Mengajar ngaji, membaca dan berhitung. Tidak lebih tidak kurang. Wajar dan sederhana.
Kami juga tidak banyak bersaudara, cuma enam orang saja. Waktu itu, enam anak belum apa-apa, karena banyak keluarga yang punya anak lebih dari selusin. Akan halnya keluarga kami, enam rasanya sudah merepotkan, mengingat ayah yang sering tak ada.
Karena itulah Mbakyu Sukanti, sulung di antara kami, langsung diambil anak oleh Bu De Oemi sejak jabang bayi. Di masa kecil, saya tak begitu mengenalnya. Yang paling saya kenal adalah abang nomor dua. Mas Suhardjo inilah yang merupakan teman sepermainan yang awet, sejak kecil hingga dewasa. Usia kami hanya terpaut dua tahun. Kemana-mana kami selalu sama, mandi sama, sekolah sama dan tidur pun sama.
Di bawah saya masih bersusun adik-adik lain. Sutikno yang persis di bawah saya adalah anak periang dan suka tertawa. Namun usianya tak panjang, dia meninggal sewaktu berusia sembilan tahun. Saya tidak tahu persis penyakitnya, kecuali sebelum meninggal dia mengalami demam panas yang tinggi.
Saya merasa kehilangan dengan kepergian Sutikno, karena dia merupakan teman bergelut dan berkejar-kejaran. Kami bertiga dengan Mas Hardjo adalah anak-anak yang bisa tertawa berlayang-layang, tetapi bisa marah-marahan berkelahi.
Dua adik kecil saya yang lain, Sudjati dan Sutari, adalah perempuan pendiam yang tidak banyak bicara. Mereka bermain berdua saja, seakan saya dan saudara-saudara lain tidak ada di dunia mereka. Jika saya nakal menggodanya, mereka tak pernah menentang. Paling-paling lari masuk rumah mencari ibu dan mengadu.
Saya sayang kepada mereka. Ayah, ibu dan semuanya. Di tengah merekalah saya bernafas, menggeliat dan belajar hidup untuk jadi manusia. Padahal apa yang terjadi esok tak pernah bisa jelas. Hidup di alam penjajahan memang demikian, tanpa kepastian akan masa depan.
Namun keluarga Brotosuwignyo tak pernah mempersoalkan yang belum terlihat. Hidup adalah kelumrahan tanpa pretensi. Jika keluarga bisa makan dan anak-anak bisa sekolah, maka mimpi akan cukup. Apa adanya saja. Kami bahkan tidak pernah merancang hal-hal muluk atau merayakan hari-hari istimewa. Satu-satunya hari besar yang membuat kami bergembira adalah Idul Fitri, saat sekolah diliburkan dan baju baru dikenakan.
Yang lain adalah kewajaran, layak sepur di atas rel.
(bersambung ke bagian 2: Mata Berkaca, Hati Tersedu)


 1. Sanggupkah Habibie?
1. Sanggupkah Habibie?