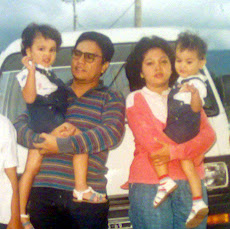Angin tipis menampar pipi saat keluar dari Korea Airlines KAL 628 di Ienchon International Airport. Kelu. Meski musim dingin datang terlambat tahun ini, tetap saja aku harus meninggikan kerah jas. Mungkin akan ditambah dengan mafela dan sarung tangan jika matahari merosot jatuh ke balik laut. Wanti-wanti yang kuterima mengatakan, di beberapa lokasi Korea Selatan, salju sudah bertabur jatuh. Dibutuhkan persiapan ekstra bagi orang yang dating ke negeri ginseng ini. Begitu juga kiranya, bagiku.
Namun dalam bus besar, terobosan dingin tidak terasa. Jong-Sub Cho, mahasiswa Korea yang mengambil Jurusan Bahasa Indonesia itu terpatah-patah mengisahkan hikayat negerinya kepadaku. Bagus juga kisah sepanjang jalan itu. Aku jadi merasa lebih lega menyusuri jalan tol di lereng gunung Chungryang, untuk menuju kawasan Songdo, tempat Hotel Ramada menjulang.
Di sana, di ruang utama hotel, seorang lagi warga Korea bersusah-payah dalam bahasa Indonesia mengelu-elukan kedatanganku. Kesopanannya bersahaja, tapi terasa terlalu mewah untuk diterima, karena aku tetap saja merasa sendiri di tengah mereka. Perjalanan ini memang tunggal, dirancang untuk satu orang dan sangat mempribadi. Karenanya, tak perlu digubris kerlingan dan cekikikan kedua perempuan muda yang menghirup mie panas di warung kecil di pojok Ramada.
Incheon yang menikamkan dingin membawaku dalam keheningannya. Di kamar memang terasa hangat, tapi aku bisa berdarah-darah dihunjam belati sepi. Tidak ada jadwal yang harus dipatuhi. Cuma dekat magrib, Jong-Sub Cho berjanji akan mengantarku ke Namdemun Sijang, pasar tradisional di kawasan kota Seoul yang berbukit. Selebihnya aku bebas dan liar seperti bola bekel. Mau gelimpangan bisa, mau jungkir balik silakan. Tergantung hasrat, terserah kaki.
Maka, lebih baik aku merentangkan kaki dan punggung di coffee-shop gelap ini, termangu-mangu sembari menghirup seseloki-dua Tia Maria untuk pemanas diri.
Adakah kedamaian itu berdiam di sini?
Namun dalam bus besar, terobosan dingin tidak terasa. Jong-Sub Cho, mahasiswa Korea yang mengambil Jurusan Bahasa Indonesia itu terpatah-patah mengisahkan hikayat negerinya kepadaku. Bagus juga kisah sepanjang jalan itu. Aku jadi merasa lebih lega menyusuri jalan tol di lereng gunung Chungryang, untuk menuju kawasan Songdo, tempat Hotel Ramada menjulang.
Di sana, di ruang utama hotel, seorang lagi warga Korea bersusah-payah dalam bahasa Indonesia mengelu-elukan kedatanganku. Kesopanannya bersahaja, tapi terasa terlalu mewah untuk diterima, karena aku tetap saja merasa sendiri di tengah mereka. Perjalanan ini memang tunggal, dirancang untuk satu orang dan sangat mempribadi. Karenanya, tak perlu digubris kerlingan dan cekikikan kedua perempuan muda yang menghirup mie panas di warung kecil di pojok Ramada.
Incheon yang menikamkan dingin membawaku dalam keheningannya. Di kamar memang terasa hangat, tapi aku bisa berdarah-darah dihunjam belati sepi. Tidak ada jadwal yang harus dipatuhi. Cuma dekat magrib, Jong-Sub Cho berjanji akan mengantarku ke Namdemun Sijang, pasar tradisional di kawasan kota Seoul yang berbukit. Selebihnya aku bebas dan liar seperti bola bekel. Mau gelimpangan bisa, mau jungkir balik silakan. Tergantung hasrat, terserah kaki.
Maka, lebih baik aku merentangkan kaki dan punggung di coffee-shop gelap ini, termangu-mangu sembari menghirup seseloki-dua Tia Maria untuk pemanas diri.
Adakah kedamaian itu berdiam di sini?